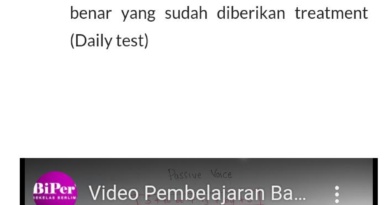Tantangan Media Massa Digital Kita
Oleh: Septiaji Eko Nugroho
Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo)
Pasca lebaran, medsos kita diramaikan dengan perdebatan yang dipicu oleh artikel di detik yang berjudul “Pemkot: Jokowi Siang Ini ke Bekasi, Dalam Rangka Pembukaan Mal”.
Di tengah polarisasi masyarakat kita yang masih tajam, berita itu tentu saja menimbulkan kehebohan. Bagi yang kontra Jokowi, ataupun kontra dengan kebijakan terkait COVID19, artikel ini menjadi bahan gorengan. “Kurva epidemiologi masih belum jelas kapan melandai, kok nekad buka mall? “. ” Kok mall duluan yang dipikirkan, kenapa bukan masjid?” Setidaknya itu yang saya lihat di beberapa status orang.
Beberapa jam kemudian muncul klarifikasi, dari Pemkot yang sama, dengan judul yang mengklarifikasi artikel pertama, “Pemkot Bekasi Luruskan soal Kunjungan Jokowi: Cek Persiapan New Normal”.
Beberapa pihak menghujat Detik, ada pula yang mengajak uninstall app Detik. Namun sepertinya Detik tidak sesial Tempo yang ratingnya sempat jatuh di angka satu koma, karena memajang gambar Presiden dengan bayangan Pinokio, dan jadi target pendukung Presiden.
Kalau kita lihat isi artikel pertama, Detik mengambil sumber langsung dari Kasubag Humas Pemkot Bekasi via telepon, dan ada rekamannya. Rekaman ini pula yang kemudian diunggah oleh Detik merespons kegusaran netizen, apakah Detik melakukan spinning?
Nah kesalahan Detik sebenarnya bukan pada spinning issue, namun karena ia mengeluarkan artikel sebelum mendapat konfirmasi dari beberapa pihak, dan ternyata secara faktual isi artikel tersebut dibantah oleh pihak istana, bahwa kedatangan Presiden tanggal 26 Mei untuk mengecek persiapan protokol new normal, bagi daerah yang selesai PSBB.
Pihak Summarecon Bekasi sendiri menyebut jika PSBB berakhir pada 8 Juni, maka mall akan siap beroperasi dengan protokol new normal.
Khan cuma selisih dua minggu? Nah begini,dalam kaidah jurnalisme presisi, kesalahan itu bukan hal kecil. Dalam berita seperti ini, konfirmasi dari pihak-pihak atau cover both sides yang diberitakan adalah syarat penting sebelum berita diturunkan, apalagi untuk topik sensitif yang berpotensi menggesek massa yang terpolarisasi.
Seorang jurnalis mestinya tahu dan bisa memperkirakan dampak dari artikel yang ia buat, termasuk mempertimbangkan konstelasi post truth yang ada.
Namun faktanya, praktek angkat dulu berita ini, nanti klarifikasi menyusul di artikel selanjutnya, kadang masih menjadi praktek media digital di negeri ini. Mereka kadang memaknai cover both sides, dengan artikel pertama biar satu sumber dulu, nanti artikel kedua dan selanjutnya dari sumber lain.
Seolah prinsip cover both sides itu sudah dipenuhi. Padahal sama sekali tidak, karena pola masyarakat mengunyah informasi tidak linear seperti itu. Berita pertama yang heboh, apalagi judulnya sensasional, itu pasti mendapat perhatian publik, mudah viral. Kalaupun ada narasumber pembanding, yang mengajak untuk lebih rasional, biasanya beritanya nggak akan lalu, jumlah share akan jauh dibanding dengan berita yang heboh. Ya itulah psikologi massa di era digital, khususnya media sosial saat ini, apalagi konsep lateral reading masih sangat awam bagi masyarakat kita.
So, saya termasuk yang menentang praktek cover both sides dalam beberapa artikel terpisah di media digital, kedua sumber harus muncul dalam artikel yang sama. Saya pernah sampaikan ini forum Kantor Staf Presiden, dan juga di forum Dewan Pers. Pedoman Media Siber kita yang lahir sebelum era Media sosial, harus diupdate melihat kekisruhan informasi yang semakin marak di masyarakat. Untuk mengajak masyarakat semakin percaya kepada media terverifikasi yang ada dalam ekosistem UU Pers, maka media wajib meninggikan kualitas jurnalistiknya, tidak ada cara lain.
Di satu sisi, saya termasuk yang sangat percaya bahwa keberadaan pers, termasuk media massa digital adalah pilar demokrasi yang harus kita pertahankan. Saya sepakat dengan tagline Washington Post, Democracy Dies in Darkness. Bahwa citizen journalism itu semakin berpengaruh, tapi ia sama sekali tidak bisa menggantikan ekosistem Pers sebagai bagian dari upaya untuk menjaga Demokrasi kita berada dalam koridor yang terang.
Tantangan untuk menjaga ekosistem Pers memang tidak mudah. Benar kita terganggu karena praktek konglomerasi media, yang membuat sebagian media partisan, dan semakin menggesek polarisasi masyarakat. Kita juga masih direcokin dengan media musiman, dibuat oleh oknum mengaku jurnalis, namun hanya terbit kalau ia mau memalak pihak tertentu, biasanya Pemda atau perusahaan di daerah yang jadi sasaran.
Tapi kita juga harus tahu, masih sangat banyak para jurnalis yang bekerja karena panggilan hati untuk setia dengan kode etik jurnalistik yang kuat. Bahkan mereka yang menolak pemberian amplop dari pihak pengundangnya. Saya bersyukur kenal banyak yang seperti ini.
Kita yang kadang sebal dengan praktek click bait media, juga mestinya ikut sebal dengan media abal-abal yang sering memperkosa artikel dari media Pers, diunggah ulang tanpa ijin ataupun lisensi apapun, diganti judul dengan yang lebih bombastis dan heboh. Dan tragisnya, kita jadi lebih tertarik baca di situs abal-abalnya ketimbang dari artikel aslinya.
Dan ada banyak lagi persoalan terkait media, khususnya media massa digital kita.
Namun saya berharap kejadian kemarin ini membuka mata supaya kita lebih peduli bagaimana bangsa ini yang masih panjang umurnya, terbantu dengan keberadaan media massa digital yang bermartabat, didukung oleh masyarakatnya yang cermat. Kalaupun jewer-menjewer itu hal biasa, bagian dari tradisi saling mengingatkan karena kasih sayang sebagai sesama anak bangsa, bukan karena kebencian dan hoaks.
(***)
Editor: Cosmas